Buzzer itu Apa Sih?
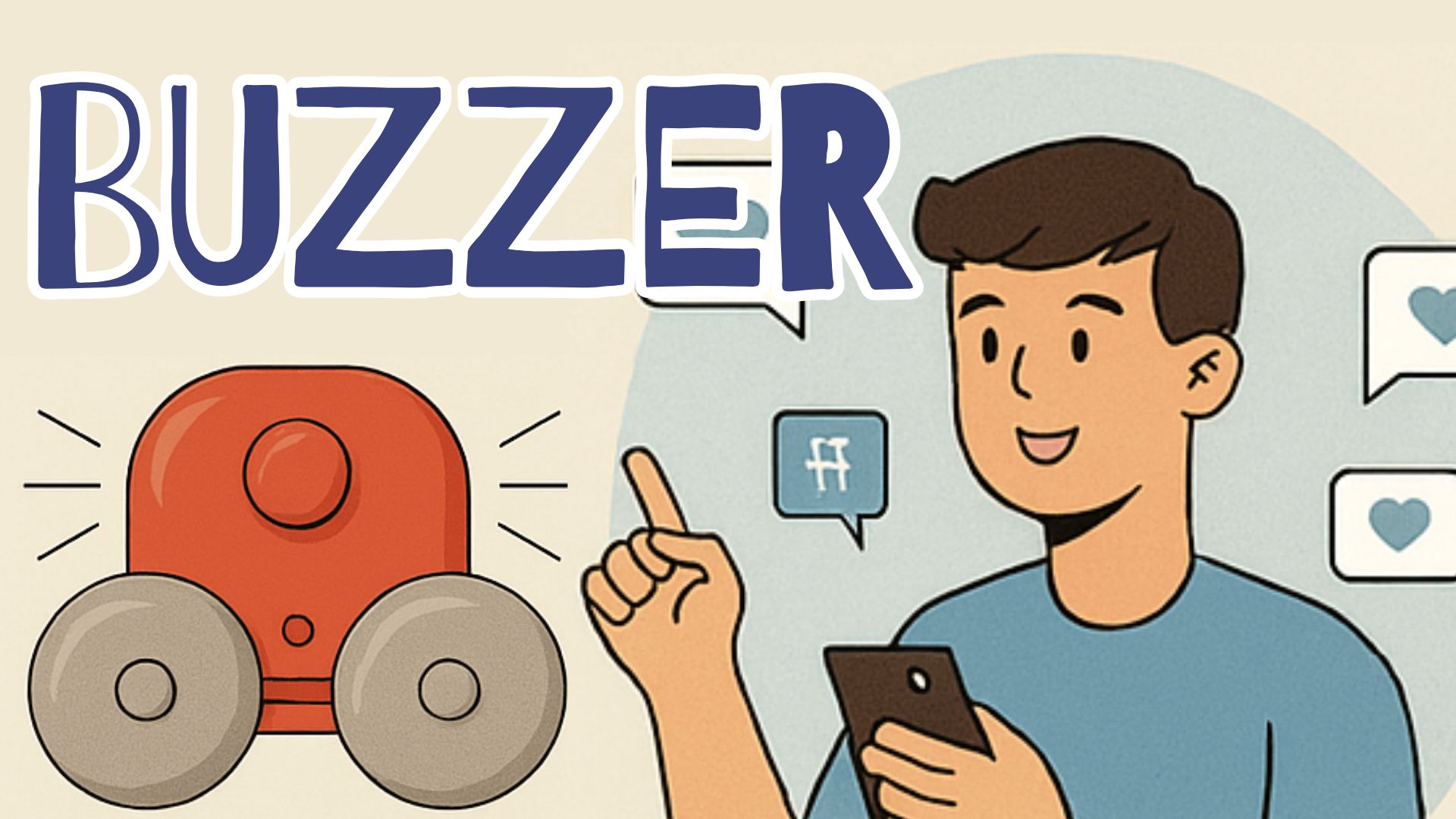
Pernah dengar kata buzzer? Kalau kita telusuri sejarahnya, kata buzzer muncul dalam konteks teknis di awal abad ke-20. Lalu populer dalam dunia hiburan lewat acara kuis TV pada era 1960-an hingga 1980-an. Baru pada 2000-an, maknanya mulai bergeser seiring naiknya kekuatan internet dan media sosial. Dan di Indonesia, istilah buzzer mulai banyak dibicarakan sejak pertengahan 2010-an, terutama menjelang pemilu dan momen politik lainnya.
Awalnya, kata ini cuma punya makna sederhana: alat kecil yang mengeluarkan bunyi berdengung, biasanya sebagai tanda. Kita bisa menemukan buzzer di sekolah sebagai bel, di dapur sebagai timer, atau dalam acara kuis sebagai tombol penjawab tercepat. Dalam makna ini, buzzer termasuk dalam kategori perangkat elektronik.
Beberapa kosakata Bahasa Inggris yang sering muncul bersama makna asli buzzer ini antara lain:
alarm, timer, bell, ring, beep, button, switch, sound, signal, device,
indicator, response, activate, click, dan buzz.
Contohnya, dalam kuis cepat-tepat, peserta akan “press the buzzer” untuk menjawab lebih dulu. Atau, saat masakan matang, oven mengeluarkan suara “buzz” sebagai tanda waktunya selesai. Semua ini menggambarkan fungsi buzzer sebagai penanda suara otomatis.
Namun, sejak era internet dan media sosial berkembang pesat, terutama setelah tahun 2000-an, kata “buzzer” mengalami perluasan makna yang signifikan.
Di Indonesia, buzzer kini lebih dikenal sebagai orang atau akun media sosial yang menyuarakan opini secara aktif dan terorganisir, sering kali untuk tujuan promosi atau politik.
Dalam konteks ini, buzzer bukan lagi benda, melainkan manusia atau akun digital yang bekerja di balik layar.
Para buzzer modern bisa bekerja untuk merek dagang, selebriti, bahkan politisi. Mereka bisa dibayar, bisa juga relawan. Peran mereka penting dalam digital marketing, branding, kampanye pemilu, atau advokasi isu tertentu.
Kata-kata Bahasa Inggris yang sering muncul dalam konteks ini antara lain:
influencer, promoter, campaigner, supporter, voice, trendsetter, advocate, content, hashtag, viral, hype, spin, exposure, platform, dan audience.
Misalnya, sebuah merek kopi kekinian meluncurkan produk baru. Untuk menarik perhatian publik, mereka menyewa para buzzer di media sosial. Tugas mereka: membuat produk itu trending, lewat unggahan foto, video, dan review positif. Dalam waktu singkat, netizen pun ikut penasaran dan jadi konsumen.
Namun, buzzer tak selalu positif. Di dunia politik, mereka sering diasosiasikan dengan penyebaran informasi yang bias, bahkan hoaks. Buzzer bisa jadi alat propaganda, mengarahkan opini publik, dan menciptakan polarisasi.
Dalam kasus seperti ini, buzzer sering dihubungkan dengan istilah negatif seperti:
manipulation, narrative, disinformation, hoax, bot, echo chamber, trolls, smear, propaganda, bias, target, influence, orchestrate, control, dan agenda.
Beberapa buzzer bahkan bukan manusia, melainkan bot—akun otomatis yang diatur untuk menyebarkan pesan tertentu dalam jumlah besar.
Fenomena ini sangat terlihat saat masa kampanye pemilu, ketika linimasa media sosial penuh dengan “pasukan buzzer” dari berbagai kubu. Mereka bekerja cepat dan masif, menyuarakan satu isu atau menyerang tokoh tertentu.
Yang menarik, kata buzzer kini punya dua wajah. Di satu sisi, buzzer bisa membantu menyebarkan informasi edukatif, misalnya saat pandemi, kampanye donor darah, atau sosialisasi kebijakan publik. Tapi di sisi lain, buzzer juga bisa jadi penyebar kebingungan dan polarisasi. Semuanya tergantung siapa yang mengendalikan dan untuk tujuan apa.
Jadi, hari ini, ketika kalian mendengar kata “buzzer”, cobalah berhenti sejenak dan pikirkan: apakah itu bel berdengung di acara kuis, atau akun Twitter dengan ribuan pengikut yang sedang menggerakkan opini publik?
